Masifnya aktivitas pertambangan di Yogyakarta memicu beragam persoalan sosial dan lingkungan. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, Selasa (7/6/2022).
Dhanil, LBH Yogyakarta, menyampaikan masifnya aktivitas pertambangan di Yogyakarta berhubungan erat dengan bingkai program pembangunan nasional. Pembangunan infrastruktur fisik, lanjutnya, menjadi sektor yang terus gencar dijalankan program pembangunan Joko Widodo dalam dua periode masa jabatanya.
Proyek infrastruktur itu memicu besarnya kebutuhan material yang mendorong masifnya aktivitas pertambangan di sejumlah daerah, khususnya di Yogyakarta. Alih-alih mendatangkan kesejahteraan, menurutnya, aktivitas pertambangan ini justru memicu sejumlah persoalan.
Konferensi pers itu dihadiri oleh sejumlah perwakilan warga terdampak pertambangan yang tergabung dalam sejumlah komunitas: PMKP (Paguyuban Masyarakat Kali Progo) Jomboran, Nanggulan, Pundak Wetan dan Wiyu; PSTA (Paguyuban Sindu Tolak Asat); Warga Banaran (Paguyuban Pelestarian Progo), Warga Srandakan (Kelompok Pelestari Progo); Warga Turgo (Paguyuban Pelestari Sumber Mata Air Hulu Sungai Boyong).
Masing-masing warga secara bergantian menyampaikan kisah pilu dampak aktivitas pertambangan di wilayah mereka.
Perwakilan warga PMPK menyampaikan, sumber air warga rusak karena aktivitas pertambangan PT. Citra Mataram Konstruksi (CMK) dan Pramudya Afgani di Sungai Progo. Perusahaan itu telah melakukan penambangan pasir sejak 2017.
Rusaknya sumber air memicu keringnya muka air sumur yang selama ini warga manfaatkan. Di Padukuhan Wiyu, Kulon Progo, misalnya, dua sumur dengan kedalaman sekira 25 meter mengalami kekeringan. Sementara di Padukuhan Jomboran, Sleman, debit air yang memasok kebutuhan rumah tangga mengalami penurunan.
Selain mengalami kekeringan, lanjutnya, aktivitas pertambangan juga memicu pencemaran air dalam rupa perubahan warna air menjadi kecoklatan sekaligus menguarkan bau.
“Padahal dulu di kampung kita itu sangat melimpah atas kekayaan alam, terutama air,” tambahnya.
Rusaknya sumber air juga memicu terganggunya saluran irigasi yang mengairi lahan-lahan pertanian warga. Ia menyampaikan, jarang warga yang berhasil memanen padi lebih dari satu kali dalam setahun.
Di samping itu, di Jomboran, tebing yang berbatasan dengan Sungai Progo mengalami longsor beberapa waktu yang lalu. Longsor itu berada di lokasi yang jaraknya sekira 15 meter dari pemukiman.
Selain rusaknya lingkungan, ia melanjutkan, masuknya tambang memecah kerukunan warga, sebab ada kelompok yang pro dan kontra terhadap tambang.
Beriringan dengan itu, suara bising dari aktivitas pertambangan menyelimuti kehidupan warga setiap harinya. Tidak hanya mengganggu kenyamanan beristirahat, suara bising juga mengganggu aktivitas belajar anak saat menjalani masa pembelajaran online karena pandemi Covid-19.
Perwakilan warga PSTA juga turut menyampaikan dampak dari aktivitas pertambangan di wilayah mereka. Hampir 10 Dusun di Kecamatan Ngemplak dan Cangkringan, Sleman, memanfaatkan air dari sumber air yang berada di kawasan Sungai Gendol wilayah mereka. Selain untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sumber air itu juga dimanfaatkan untuk mengairi lahan pertanian dan kolam ikan.
Namun saat ini, warga sedang dirundung perasaan cemas akan hilangnya sumber air karena tambang pasir di kawasan Sungai Gendol. Menurut perwakilan warga PSTA, setidaknya mereka mesti menanggung kerugian finansial sebesar Rp. 10 milyar dalam setahun bila sumber air itu hilang.
Kisah serupa juga dialami oleh warga di Hulu Sungai Boyong, Turgo, Sleman. Perwakilan warga Turgo menyampaikan Padukuhan Ngandong, Sleman, salah satu bagian dari paguyuban, telah mengalami kekeringan karena aktivitas pertambangan pasir.
Salah satu perusahaan yang melakukan aktivitas pertambangan di kawasan itu ialah PT Sukses Ketiban Mulyo. Menurutnya, perusahaan itu mendapat izin pertambangan seluas 5-10 ha dengan kedalaman 10 meter. Padahal, Sungai Boyong telah mengalami penurunan sedalam 5 dan memicu turunnya debit air sekira 40%.
Karena itu, menurutnya, bila aktivitas pertambangan terus dilakukan, semakin luasnya kerusakan sumber air tak dapat dihindari. Ia menambahkan, mata air di kawasan itu bukan hanya dimanfaatkan warga sekitar, melainkan juga menjadi pemasok air bagi tiga kabupaten di Provinsi Yogyakarta.
“Di samping sebagai penyanggah sumber mata air, wilayah kami sebagai daerah satu tangkapan resapan air hujan di Kabupaten Sleman yang memenuhi air tanah di Kabupaten Sleman, Kota, bahkan sampai ke Bantul,” tuturnya.
Beralih ke pesisir selatan Yogyakarta. Perwakilan warga Desa Banaran, Kulon Progo, yang tergabung dalam Paguyuban Pelestarian Progo menyampaikan sumur dan saluran irigasi mengalami kerusakan. Kedua hal itu disebabkak oleh aktivitas pertambangan pasir di Sungai Progo yang berada di sekitar wilayah mereka.
Rusaknya sumber air, bukan hanya memicu keringnya pasokan air rumah tangga, melainkan mengganggu pasokan air ke lahan-lahan pertanian warga.
Selain itu, aktivitas pertambangan juga telah memicu merangseknya air laut memasuki aliran Sungai Progo. Hal ini mengakibatkan terjadinya perubahan kualitas air sungai, yang sebelumnya air tawar menjadi air asin. Ia menyampaikan, warga khawatir bila air sungai yang menjadi asin itu menyerap ke sumur warga.
“Ini bencana besar kalau sumur warga dari satu kelurahan 13 padukuhan itu airnya asin semua. Itu sungguh kerugian yang tidak bisa dinominalkan lagi,” tuturnya.
Saat ini, telah ada 10 izin perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah tersebut. Namun, muncul kabar bahwa izin baru atas nama PT. Sidokabul Mandiri Karya akan melakukan aktivitas pertambangan seluas 36 ha. Izin pertambangan itu berada di atas lahan-lahan warga dengan letter C dan sebagian telah bersertifikat.
“Kalau sampai terjadi tentu akan terjadi penolakan yang sangat besar di kelurahan kami,” tuturnya.
Tambang melanggar administrasi
Abimanyu, Wahana Lingkungan HIdup Indonesia (WALHI) Yogyakarta, menyampaikan meskipun banyak di antara aktivitas pertambangan itu mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) namun tidak menjamin terhindar dari hadirnya kerusakan.
Pasalnya, proses penyusunan izin seringkali tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Salah satunya, warga seringkali tidak dilibatkan dalam proses penyusunan izin pertambangan.
Hal ini dialami oleh warga dari paguyuban PSTA. Menurut perwakilan PSTA, CV Canyon, salah satu perusahaan tambang di wilayah itu, memperoleh izin tanpa sepengetahuan warga. Proses perizinan hanya melibatkan sebagian warga dan pemerintah kelurahan. Bahkan, di tengah penolakan yang dilakukan warga, pihak kelurahan justru memberikan izin kepada perusahaan untuk mendirikan sekretariat atau kantor perusahaan di daerah Ngemplak dan Cangkringan.
Selain IUP, pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan ialah penyimpangan izin penggunaan alat berat dan luas wilayah.
Di Jomboran, misalnya, dalam izin yang diajukan oleh perusahaan ialah hanya menggunakan dua eskavator. Namun, pada praktiknya mereka menggunakan empat eskavator dalam aktivitas pertambangan.
Hal tersebut juga terjadi di Dusun Banaran. Dalam izin yang diajukan oleh sejumlah perusahan pertambangan di daerah itu ialah penggunaan alat berat untuk pertambangan permukaan. Namun, pada kenyataannya, perusahaan juga menggunakan mesin sedot dengan kapasitas besar.
Di Dusun Banaran, pelanggaran administrasi bukan hanya terjadi dalam penggunaan alat pertambangan. Luas wilayah pertambangan seringkali lebih besar ketimbangan yang diajukan dalam proses perizinan.
“Setiap izin pasti ada luasan dan titik koordinatnya. Tetapi, banyak sekali penyimpangan luas wilayah tambang,” tuturnya.
Ia menambahkan, perusahaan yang telah mengantongi izin pertambangan pada dasarnya memiliki kewajiban untuk melakukan reklamasi. Namun, hal itu tidak pernah mereka penuhi. Pada akhirnya, lubang-lubang bekas tambang dibiarkan menganga begitu saja. Bila aktivitas demikian terus dilakukan, ia khawatir tanggul penahan aliran sungai akan jebol.
“Kalau tanggul sempat jebol, maka satu kelurahan itu akan terancam hilang,” tambahnya.
Beriringan dengan itu, ia menyayangkan sikap pemerintah yang melakukan pembiaran terhadap beragam pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pertambangan.
Menanggapi fenomena tersebut, Abimanyu memandang, “Makanya tidak heran seringkali aktivitas penambangan merusak lingkungan, padahal secara official itu mereka mengantongi izin.”
Kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan
Dhanil menyebut, masifnya aktivitas pertambangan di Yogyakarta telah memicu terjadinya perebutan ruang hidup.
Sebagaimana disampaikan di atas, aktivitas pertambangan seringkali menuai penolakan dari warga. Selain karena tertutupnya akses partisipasi warga dalam proses penyusunan izin, ancaman kerusakan sosial dan lingkungan juga menjadi alasan munculnya penolakan. Penolakan itu, lanjutnya, seringkali berbuntut intimidasi dan kriminalisasi.
“Di samping kerusakan lingkungan juga banyak sekali upaya kriminalisasi baik dilakukan oleh pihak korporasi ataupun pemerintah, dalam hal ini negara,” tuturnya.
Intimidasi menimpa sejumlah warga PSTA ketika melakukan aksi menolak pertambangan di wilayah mereka. Dalam aksi itu, aparat kepolisian menurunkan spanduk-spanduk yang dipasang warga di sekitar Sungai Gendol.
Tidak hanya itu. Aparat kepolisian juga mendatangi warga untuk memaksa mereka berhenti melakukan penolakan. Hal tersebut dialami oleh perwakilan warga PSTA yang menjadi pembicara dalam konferensi pers.
“Saya didatangi [polisi] jam 10 malam, diintimidasi, untuk tidak ikut-ikutan dalam penolakan tambang,” tutur perwakilan warga PSTA.
Selain itu, ia juga menyampaikan salah satu warga PSTA yang berprofesi sebagai guru mendapatkan panggilan dari Dinas Pendidikan Provinsi Yogyakarta karena teridentifikasi terlibat dalam aksi penolakan tambang di wilayahnya.
Sementara kriminalisasi dialami oleh warga Jomboran. Sejak satu tahun terakhir, tiga orang warga Jomboran mendapatkan pemanggilan dari Polres Sleman karena dituding menghalangi aktivitas pertambangan. Saat ini, status dari ketiga warga itu telah naik menjadi tersangka dan menjalani proses penyidikan.
Menurut Dhanil, setiap upaya mempertahankan ruang hidup itu pada dasarnya selaras dengan Undang Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Pasal 6 ayat 1 dalam UU menyebutkan, setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Karena itu, baginya, warga yang melakukan penolakan itu dapat disebut sebagai pejuang lingkungan.
Dhanil melanjutkan, mengacu pada UU PPLH Pasal 66, setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.
“Bukannya memberi perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak warga, tapi justru terkadang dalam banyak kasus, negara melalui aparat keamanan kemudian ikut terlibat dalam proses kriminalisasi, dalam proses intimidasi, dan seterusnya,” pungkasnya.
Bayu Maulana

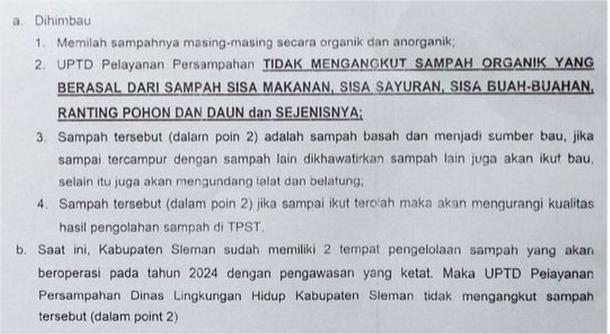









0 Comments